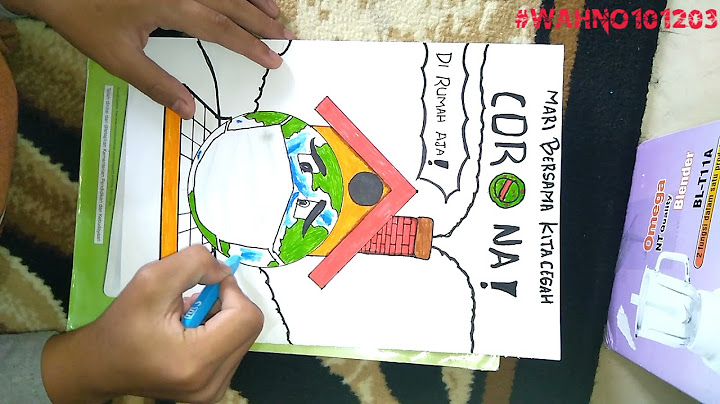Sebuah Materi Podcast “Bincang Hukum” Narasumber : Kenny Santiadi – Relawan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR Pembahasan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat akan dibagi menjadi 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang konstitusional dan sudut pandang peraturan perundang-undangan. Sudut pandang hukum nasional akan dikaitkan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak. Hak kebebasan berpendapat ini bisa memiliki berbagai macam tujuan, tapi dalam tulisan ini akan difokuskan dengan penggunaan hak kebebasan berpendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mencerdasarkan kehidupan bangsa, dapat diupayakan dengan perlindungan kebebasan berpendapat. Secara teoritik untuk menjelaskan hak kebebasan berpendapat (freedom of speech), bisa merujuk pendapat dari Frederick Schauer. Schauer berpendapat,[1] “…when a free speech is accepted, there is a principle according to which speech is less subject to regulation (within a political theory) than other forms of conduct having the same or equivalent effects. Under a free speech principle, any govermental action to achieve a goal, whether that goal be positive or negative, must provide stronger justification when the attainment of that goal…” (…ketika kebebasan berpendapat diterima, ada prinsip yang menyatakan bahwa pendapat kurang tunduk pada regulasi (dalam teori politik) daripada bentuk perilaku lain yang memiliki efek yang sama atau setara. Berdasarkan prinsip kebebasan berbicara, setiap tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan, apakah tujuan itu positif atau negatif, harus memberikan justifikasi yang lebih kuat ketika pencapaian tujuan itu …) Penjelasan di atas tepat untuk menjelaskan kebebasan berpendapat, sebab Schauer menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan dengan pendapat yang tidak penuh pada aturan tertentu, bisa digunakan untuk tindakan pemerintah, dan memiliki tujuan tertentu. Menimbang beberapa ciri yang disampaikan untuk menjelaskan kebebasan berpendapat, maka penting untuk melihat kesamaannya sesuai dengan regulasi di Indonesia. Kesamaan tersebut untuk mencari tahu terkait dengan tujuan dari penggunaan kebebasan berpendapat di Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Jaminan perlindungan hak kebebasan meyampaikan pendapat ini diatur secara umum dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut. Perlindungan kebebasan berpendapat diatur secara spesifik dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)” Kemerdekaan pendapat termasuk hak yang sangat dasar, sebab hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan bagian menimbang pada UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk mengindikasikan bahwa pendapat bisa disampaikan tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. Pendapat yang disampaikan tentu membutuhkan ruang sebagai sarana ekspresi dari pendapat yang hendak disampaikan. Pendapat yang hendak diekspresikan bisa disampaikan dalam ruang publik, Pasal 1 angka 2 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan, “Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang.” Ruang publik yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat menjadi penting, sebab dengan pendapat yang disampaikan di ruang publik bisa memenuhi dua aspek ontologis (berkaitan dengan keadaan). Aspek ontologis pertama yang bisa dipenuhi berkenaan dengan ekspresi kemanusiaan (express themselves) dan keunikan identitas (unique identity). Pemenuhan dua aspek ontologis ini sangat penting, mengacu pada pendapat Arendt,[2] “Grounding speech as a distinctive characteristic of human beings that express themselves publicly might provide a non-consequentialist aspect to the theory of personal development. In an Arendtian sense, one might attribute to speech an existential signifiance: only by way of speech do human being express their unique identity among others in the public realm.” (Sebagai ciri khas manusia yang mengekspresikan diri secara terbuka dapat memberikan aspek non-konsekuensialis pada teori pengembangan pribadi. pengertian Arendtian, orang mungkin mengaitkan ucapan dengan makna eksistensial: hanya dengan cara bicara manusia mengekspresikan identitas unik mereka di antara yang lain di ranah publik.) Pendapat yang dikemukakan oleh Arendt bisa menjembatani tentang hak kebebasan berpendapat dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Arendt mengkategorikan kebebasan berpendapat terkait dengan eksistensi manusia yang signifikan untuk mengungkapkan keunikan identitasnya. Pendapat tersebut jika ditarik lebih jauh bisa ditafsirkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang atau pelarangan kebebasan berpendapat secara mutlak, berdampak manusia tidak dapat mewujudkan eksistensinya. Keterbatasan dalam perwujudan eksistensi manusia, sama halnya dengan membatasi juga upaya untuk membuat manusia lebih cerdas. Hasil akhir dari berbagai macam pembatasan kebebasan berpendapat, tanpa menimbang eksistensi manusia dapat berakhir dengan komunitas yang eksklusif, jauh dari kata inklusif. Pendapat dari Arendt, diakui juga dalam Pasal 4 huruf c UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, “Mewujudkan iklim yang kondusif bagi partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.” Kreativitas dan partisipasi merupakan bagian dari iklim demokrasi. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat termasuk hal yang penting. Pengabaian terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat bisa menyebabkan menurutnya tingkat partisipasi dan kreativitas dari warga negara. Cara untuk menyampaikan pendapat juga aspek yang tidak boleh dilupakan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Arendt berpendapat ruang tersebut dinamakan sebagai ruang penampakan (ersheinungsraum),[3] “Ruang penampakan terjadi di tempat orang-orang saling berinteraksi dengan bertindak dan berbicara; ruang itulah yang menjadi dasar pendirian dan bentuk negara…Ruang itu ada secara potensial pada setiap himpunan orang, memang hanya secara potensial; ia tidak secara niscaya diaktualisasi di dalam himpunan itu dan juga tidak dipastikan untuk selamanya atau untuk waktu tertentu…” Partisipasi dan kreativitas ini tidak jarang dibungkam, padahal dengan terwujudnya kedua hal ini bisa mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kejadian paling baru terjadi teror kepada Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (CLS FH UGM). Pembicara di CLS FH UGM yang berjudul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sitem Ketatanegaraan”. Pembicara diskusi tersebut Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum mendapat teror dari tanggal 28 Mei 2020 hingga 29 Mei 2020, selain pembicara yang mendapat teror, moderator dan narahubung juga diteror.[4] Meskipun pelaku teror belum terungkap, kejadian itu menunjukan bahwa diskusi ilmiah tidak bebas dari teror pihak-pihak tertentu. Simpulan yang dapat diberikan atas paparan di atas terkait dengan hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang patut diperhatikan. Perhatian yang diberikan terhadap hak menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang pada akhirnya berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak warga negara bisa menikmati sistem pendidikan konvensional, melainkan tingginya atensi partisipasi publik merupakan hal yang harus diperhatikan. Tersedia di Anchor Google Podcast Referensi: [1] Schauer, Frederick. 1982. Free Speech: A Philosophical Inquiry. New York: Cambridge University Press. [2] Arendt, Hannah. 1958. The Human Condition. Chicago: Chicago University Press. [3] Hardiman, F. Budi. 2010. Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius. [4] Pradito Rida Pertana, UGM Ungkap Teror Gegara Diskusi: Ojol ‘Serbu’ Rumah, Ancaman Pembunuhan, https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5034266/ugm-ungkap-teror-gegara-diskusi-ojol-serbu-rumah-ancaman-pembunuhan (diakses pada tanggal 27 Juli 2020). Dasar Hukum:
Reformasi 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan ini merupakan salah satu capaian yang menjadi kesuksesan kisah gerakan Reformasi. Negara pasca-Orde Baru diharapkan akan bersikap lebih positif terhadap kondisi HAM. Meski Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun setelah runtuhnya Orde Baru, namun ternyata, hingga saat ini, belum membuahkan perubahan yang cukup siginifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya menyangkut kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi. Terdapat 4 catatan yang menjadi gambaran bahwa pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam bingkai kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi masih butuh pemenuhan dan perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Keempat catatan tersebut yaitu: Pertama, terkait kebebasan pers, reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia. Meskipun terdapat UU Pers, namunkelemahan perlindungan pers masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis baik itu secara fisik atau non fisik. LBH Pers dari tahun 2003 sampai akhir 2017 setidaknya mencatat ada 732 kasus kekerasan kepada jurnalis baik itu fisik maupun non fisik. Menurut LBH Pers, terdapat 2 faktor yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang, yaitu Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun penyelesaianya lama bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut dan pihak jurnalis atau perusahaan medianya memilih mendiamkan dan tidak mau berurusan dengan proses hukum. Belum lagi, masih terdapat pembatasan-pembatasan hak atas informasi di Papua seperti Kasus kekerasan jurnalis lokal maupun pelarangan peliputan jurnalis asing. Frekuensi publik masih disalahgunakan untuk kepentingan partai politik, kelompok maupun pribadi tertentu. Isi siaran yang masih menayangkan kekerasan, tidak sensitif gender maupun tidak ramah anak. Isi siaran TV sangat Jakartasentris. Sistem siaran jaringan (SSJ) tidak dilaksanakan dengan benar. Serta, kepemilikan stasiun TV yang mengindikasikan pelanggaran UU Penyiaran no 32/2002. Kedua, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang masih menunjukkan masa suram pasca 20 tahun reformasi. Tindak pidana Cyber Crime di Indonesia pada tahun 2016 terdapat peningkatan kasus tindak pidana penghinaan sebanyak hampir 2 kali lipat (Tahun 2016 = 708 laporan) dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2015 = 485 laporan). Lalu, setidaknya ada 49 kasus di 2017 yang dilaporkan dengan menggunakan UU (Undang-Undang) Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat warga negara, yaitu pasal-pasal penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tertuang dalam UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, pasal makar yang justru menyasar kepada ekspresi politik, penodaan agama, penodaan agama yang marak digunakan pada selang 2 tahun belakangan, dan juga pengesahan UU MD3. Di sisi lain, terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mengancam kebebasan sipil dari Rancangan UU yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR. Salah satu yang paling mengerikan adalah RKUHP yang saat ini sedang dibahas. Pertama, tentang kejahatan ideologi negara yang masih multitafsir dan samar. Kedua, mengenai tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden yang dalam KUHP telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Ketiga, terkait dengan penghinaan terhadap pemerintah yang sah atau biasa disebut haatzaai artikelen, yang juga dalam KUHP telah didekriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2017. Keempat, BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, atau lazim disebut Contemp of Court (CoC) dimana larangan untuk mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan yang diatur dalam pasal 305 huruf E tidak ada ukuran yang jelas serta indikator yang terukur. Kelima, terkait dengan delik penghinaan, yang meningkatnya ancaman pidana dan ketiadaan alasan pembenar yang cukup. Hal-hal diatas jelas akan mengancam penghormatan dan perlindungan hak – hak dan kebebasan berekspresi dari warga negara. Pada 2017, Badan Pusat Statistik merilis indeks demokrasi Indonesia yang menilai bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Penurunan indeks demokrasi yang dinyatakan oleh pemerintah merupakan peringatan dini tentang upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, terkait kebebasan berkumpul, berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR, sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara. Kedua belas kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organisasi, justru direspon berbeda. Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah disahkan juga oleh DPR RI menjadi UU No. 16 Tahun 2017, untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam UU Ormas. Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi kita. Keempat, hak atas informasi, untuk menjamin pemenuhan atas perolehan informasi untuk masyarakat terkait informasi publik, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di dalam UU memang telah diatur kategorisasi-kategorisasi informasi tersebut namun pada prakteknya terjadi kesumiran bahkan inkonsistensi oleh Badan Publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang sudah sangat jelas informasi tersebut kategori informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat. Kesumiran dan inkonsistensi tersebut dapat dilihat pada proses uji konsekuensi terhadap suatu informasi. Selain itu proses uji konsekuensi juga tidak didukung oleh pedoman teknis yang memadai. Hal tersebut tentu berdampak dalam penghambatan dan bahkan melanggar proses perlindungan hak memperoleh informasi masyarakat. Saat ini terdapat informasi bahwa pihak Sekretariat Negara telah melakukan uji konsekuensi terhadap draft/naskah Rancangan Undang-Undang yang bertujuan agar naskah RUU tersebut dikategorisasikan menjadi informasi yang dikecualikan. Di sisi lain, permohonan permintaan dokumen hasil Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir yang dikabulkan oleh Hakim Ajudikasi KIP yang menyatakan Dokumen TPF Munir termasuk informasi publik dan wajib diserahkan kepada masyarakat justru direspon berbeda oleh pemerintah. Pihak pemerintah berdalih bahwa dokumen tersebut telah hilang sehingga tidak dpaat diserahkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak hanya menghambat pemenuhan hak atas informasi masyarakat tapi juga menghambat upaya penegakan hukum yang menjadi kepentingan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kasus pengungkapan praktik korupsi yang dilakukan oleh whistle blower di berbagai daerah namun realitanya bukannya dilindungi justru menjadi sasaran pelaporan balik bahkan terjerat sendiri dengan kasus korupsi yang dilaporkannya. Seperti contoh kasus Daud Ndakularak dan Stanly Handry Ering. Melihat 4 (empat) poin catatan diatas, Koalisi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi merekomendasikan:
Koalisi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi LBH Pers, AJI Jakarta, ICJR, dan Safenet
|

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#4
#5
#6
#7
Top 8 apa itu benedict dan biuret? 2022
1 years ago#8
#9
#10
Top 6 apa itu self pick up grabfood? 2022
2 years agoPeriklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 toptenid.com Inc.