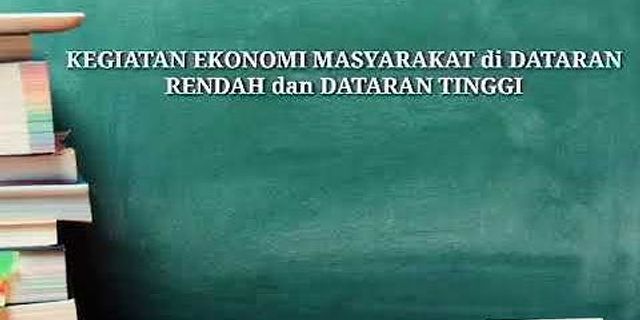Mulai belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU 23/2004, aparat penegak hukum belum memahami konsep relasi kuasa, hingga kesulitan menghadirkan alat bukti dan menghadirkan korban di persidangan. Diharapkan, nantinya banyak jaksa yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan. Bacaan 6 Menit
 Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap merugikan secara fisik dan psikis. Bahkan perempuan dan anak yang menjadi korban malah makin terpojokan ketika berhadapan dengan hukum. Untuk itu, terbitnya Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, bisa menjadi angin segar bagi penegakan hukum, khususnya bagi saksi dan korban dalam perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Bestha Inatsan Ashilla mengatakan perempuan memiliki kecenderungan menjadi korban tindak pidana dibandingkan dengan pria. Dia mencontohkan 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2017 pun, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari dengan kecenderungan usia korban yang belia. Dia menilai dalam praktik penegakan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum kerap menemui beragam persoalan. Persoalan tersebut malah menambah beban penderitaan ketika menjalani proses hukum. Setidaknya terdapat delapan persoalan perempuan berhadapan dengan hukum. (Baca Juga: 3 Alasan Terbitnya Pedoman Kejaksaan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak)
Pelaku kerapkali orang yang dekat atau dikenal korban. Merujuk data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2020, ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), didominasi kekerasan fisik sebesar 43 persen. Kemudian kekerasan seksual sebesar 25 persen, psikis 19 persen. Sedangkan hasil survei IJSR dan Infid periode 2020 ditemukan kekerasan terhadap istri sebesar 59 persen. Sementara kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 21 persen. Selain itu, mayoritas responden mengalami kekerasan seksual di tempat privat. Seperti di rumah sebesar 34 persen, kantor 10,8 persen, sekolah 20 persen, dan media sosial sebesar 12,1 persen. Dia menerangkan, UU 23/2004 mengatur tentang pidana tambahan yakni berupa program konseling bagi pelaku dan pembatasan jarak. Namun praktiknya oleh penegak hukum sulit implementasinya karena belum ada peraturan turunan, fasilitas/ sarana dan prasarana. “Serta tidak adanya lembaga yang diberi amanat secara khusus untuk menjadi penyedia layanan,” ujar Bestha Inatsan Ashilla dalam sebuah webinar bertajuk “Peluncuran Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana”, Senin (8/3/2021). Tapi, dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021 terdapat solusi dalam mengimplementasikan UU 23/2004. Selain pidana pokok tambahan, penuntut umum dalam rekuisiotornya dapat meminta hakim agar menjatuhkan pidana tambahan yakni berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu. Kemudian program konseling di bawah pengawasan rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling. Page 2Mulai belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU 23/2004, aparat penegak hukum belum memahami konsep relasi kuasa, hingga kesulitan menghadirkan alat bukti dan menghadirkan korban di persidangan. Diharapkan, nantinya banyak jaksa yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan. Bacaan 6 Menit Selanjutnya, penuntut umum mencantumkan tuntutan agar hakim menghukum terdakwa melaksanakan pidana tambahann konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Bila dokumen asesmen pemeriksaan perilaku pelaku (criminal profiling) memberi rujukan untuk pelaksanaan pidana tambahan konseling di bawah lembaga tertentu.
Relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam hal relasi antar gender inilah berakibat merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Misalnya, ayah dan anak, guru dan murid, kepala sekolah dan guru, pembatu rumah tangga dengan majikan, pegawai dengan pimpinan. Relasi kuasa itulah membuat korban tidak bisa melawan/menolak karena kekuasaan yang ada pada seseorang. Menurutnya, hasil temuan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) periode 2016 menunjukan kekerasan seksual terjadi tak hanya adanya ancaman kekerasan, tapi juga disebabkan adanya bujuk rayu, daya, tipu muslihat, membuat tidak berdaya psikis. Seperti diberi/dijanjikan uang, menjanjikan posisi/jabatan, menjanjikan ilmu, kesembuhan, diancam akan memutus relasi, mengancam memberhentikan dukungan finansial, menggunakan alkohol. Definisi perkosaan Pasal 285 KUHP mensyaratkan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan. Solusi terkait relasi kuasa dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021, pelaku kejahatan cabul atau persetubuhan dilakukan tanpa adan paksaan kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan posisi perempuan dan anak atau terdapat relasi kuasa, sehingga pelaku dapat dituntut pidana menggunakan Pasal 294 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Menurutnya, streotip merupakan perempuan baik yang tak mungkin menjadi korban pelecehan. Sebaliknya perempuan yang keluar malam bukanlah perempuan baik-baik. Perempuan dianggap berperan terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan victim blaming merupakan korban disalahkan ketika perempuan tak melakukan perlawanan dalam kasus kekerasan seksual dianggap memberikan persetujuan. Kemudian perempuan kerap disalahkan akibat menggunakan pakaian terbuka dan keluar malam. Termasuk meragukan kesaksian korban lantaran memiliki hubungan dengan pelaku. “Adanya persepsi perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tidak pidana,” ujarnya.
Dalam praktiknya, pelaku memang diganjar hukuman penjara. Namun, kata Bestha, aparat penegak hukum belum mempertimbangkan dampak fisik dan psikis yang dialami perempuan korban, pemberian ganti rugi, dan proses pemulihan yang terpadu. Page 3Mulai belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU 23/2004, aparat penegak hukum belum memahami konsep relasi kuasa, hingga kesulitan menghadirkan alat bukti dan menghadirkan korban di persidangan. Diharapkan, nantinya banyak jaksa yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan. Bacaan 6 Menit Kemudian, ketiadaan ahli seperti psikolog dan visum et psikiatrikum yang dihadirkan dalam persidangan untuk menilai kondisi korban. Padahal, keberadaan ahli dibutuhkan dalam hal menjelaskan dampak psikologis (visum et psikiatrikum). Mekanisme pemeriksaan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Selain itu, belum semua dakwaan dan tuntutan memuat analisis sosial, penilaian/assessment perempuan, dan anak pelaku.
Aparat penegak hukum tidak mengakui atau tidak mengizinkan pendamping korban mendampingi selama proses hukum. Padahal pemberian pendampingan terhadap korban telah diatur gamblang dalam Pasal 10 huruf d UU 23/2004 yang menyebutkan, “Korban berhak mendapatkan: d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Begitu pula dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Menurut Bestha, sebanyak 61.7% masyarakat Indonesia cenderung menggunakan mekanisme informal dalam menyelesaikan perkara. Seperti aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Sementara 32.1 persen menggunakan mekanisme formal. Seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Selanjutnya 39.4 persen, masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, tidak melakukan upaya apapun menyelesaikan permasalahan hukumnya. Setidaknya terdapat alasan menempuh mekanisme formal dianggap bakal membuat permasalahan semakin rumit sebesar 42%. “Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian hukum secara formal masih rendah,” kata dia.
Dia menilai paradigma penegakan hukum dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berorientasi punitive dan retributive. Alhasil, perlunya pendekatan secara restorative justice terutama terkait pemulihan korban. Ironisnya, belum semua dakwaan dan tuntutan memuat penilaian/assessment kerugianyang dialami korban. Untuk itu, perlunya jaksa untuk mencantumkan penilaian atas kerugian korban dan ditindaklajuti dengan dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan.
Pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan acapkali terhambat. Penyebabnya, akibat minimnya saksi dan alat bukti. Keengganan saksi memberi keterangan akibat adanya ancaman keselamatan maupun trauma. Nah korban kerapkali masih diperiksa secara bersamaan dengan pelakku atau terdakwa. Page 4Mulai belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU 23/2004, aparat penegak hukum belum memahami konsep relasi kuasa, hingga kesulitan menghadirkan alat bukti dan menghadirkan korban di persidangan. Diharapkan, nantinya banyak jaksa yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan. Bacaan 6 Menit Merujuk Pasal 173 KUHAP, hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Namun untuk mengusahakan pemberian keterangan yang bebas dan tanpa tekanan, sebaiknya pelaku dan korban juga diperiksa secara terpisah. Seperti menggunakan pemeriksaan terpisah melalui audio visual jarak jauh atau perekaman elektronik. Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, Siti Mazumah menilai perempuan dan anak menjadi pihak yang dirugikan secara langsung dan paling menderita akibat tindak pidana yang terjadi. Tak jarang kerugian fisik, materi, ataupun psikis dialami korban seumur hidup. Dalam pengalaman LBH Apik mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum, jaksa yang baik dan memiliki perspektif korban hanya tentang keberuntungan. “Ketika dia menemukan jaksa yang baik, maka perlakuan dalam proses dakwaan dan tuntutan pasti akan memperhitungkan dampak dan kerugian yang dialami korban,” ujarnya. Namun tak jarang, jaksa hanya melihat korban sekali saja di persidangan pada saat pemberian keterangan saksi. Setelahnya, korban tak lagi mendapat perhatian. Sebab, jaksa menganggap tugasnya menghadirkan korban telah selesai. Dia berharap nantinya banyak jaksa yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan. “Oleh karenanya aturan berupa Pedoman Kejaksaan 1/2021 menjadi sistem bagi semua jaksa yang melakukan tugas penuntutan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum,” katanya. Page 5Mulai belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU 23/2004, aparat penegak hukum belum memahami konsep relasi kuasa, hingga kesulitan menghadirkan alat bukti dan menghadirkan korban di persidangan. Diharapkan, nantinya banyak jaksa yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan. Bacaan 6 Menit
 Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap merugikan secara fisik dan psikis. Bahkan perempuan dan anak yang menjadi korban malah makin terpojokan ketika berhadapan dengan hukum. Untuk itu, terbitnya Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, bisa menjadi angin segar bagi penegakan hukum, khususnya bagi saksi dan korban dalam perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Bestha Inatsan Ashilla mengatakan perempuan memiliki kecenderungan menjadi korban tindak pidana dibandingkan dengan pria. Dia mencontohkan 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2017 pun, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari dengan kecenderungan usia korban yang belia. Dia menilai dalam praktik penegakan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum kerap menemui beragam persoalan. Persoalan tersebut malah menambah beban penderitaan ketika menjalani proses hukum. Setidaknya terdapat delapan persoalan perempuan berhadapan dengan hukum. (Baca Juga: 3 Alasan Terbitnya Pedoman Kejaksaan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak)
Pelaku kerapkali orang yang dekat atau dikenal korban. Merujuk data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2020, ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), didominasi kekerasan fisik sebesar 43 persen. Kemudian kekerasan seksual sebesar 25 persen, psikis 19 persen. Sedangkan hasil survei IJSR dan Infid periode 2020 ditemukan kekerasan terhadap istri sebesar 59 persen. Sementara kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 21 persen. Selain itu, mayoritas responden mengalami kekerasan seksual di tempat privat. Seperti di rumah sebesar 34 persen, kantor 10,8 persen, sekolah 20 persen, dan media sosial sebesar 12,1 persen. Dia menerangkan, UU 23/2004 mengatur tentang pidana tambahan yakni berupa program konseling bagi pelaku dan pembatasan jarak. Namun praktiknya oleh penegak hukum sulit implementasinya karena belum ada peraturan turunan, fasilitas/ sarana dan prasarana. “Serta tidak adanya lembaga yang diberi amanat secara khusus untuk menjadi penyedia layanan,” ujar Bestha Inatsan Ashilla dalam sebuah webinar bertajuk “Peluncuran Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana”, Senin (8/3/2021). Tapi, dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021 terdapat solusi dalam mengimplementasikan UU 23/2004. Selain pidana pokok tambahan, penuntut umum dalam rekuisiotornya dapat meminta hakim agar menjatuhkan pidana tambahan yakni berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu. Kemudian program konseling di bawah pengawasan rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling. |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#4
#5
#6
#7
Top 8 apa itu benedict dan biuret? 2022
1 years ago#8
#9
#10
Top 6 apa itu self pick up grabfood? 2022
2 years agoPeriklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 toptenid.com Inc.