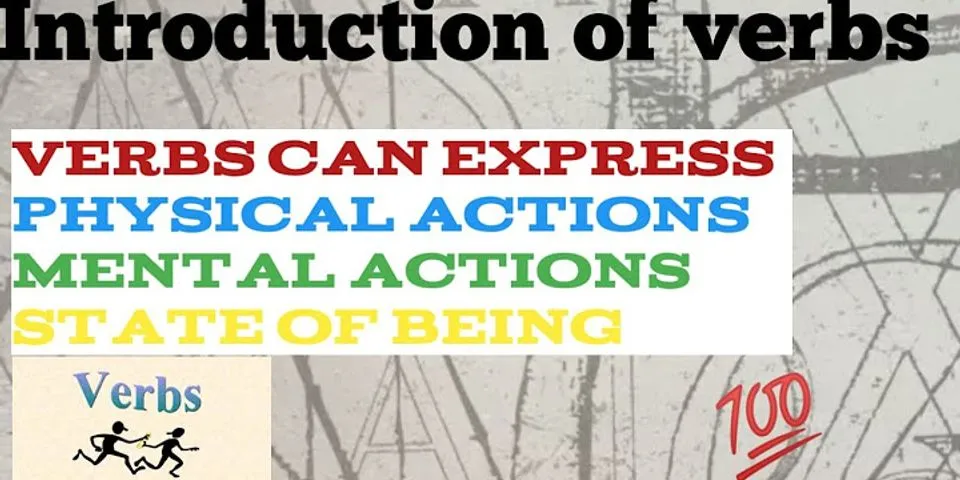|
Show JAKARTA, KOMPAS.com - Inovasi strategis untuk menahan laju kenaikan suhu global terus dikembangkan supaya dapat mencegah dampak perubahan iklim yang fatal bagi peradaban. Setelah Perjanjian Paris yang mengikat komitmen warga dunia untuk menurunkan kadar emisi global pada 2015, sebanyak 40 negara perwakilan dari seluruh dunia kembali memperbarui komitmennya dalam Leaders’ Summit on Climate yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada 22-23 April 2021 secara virtual. Hal tersebut dilakukan karena dampak pemanasan global kini kian terasa. Kekeringan ekstrem yang melanda Amerika Selatan, kebakaran hutan di Amerika Serikat, banjir bandang di Afrika dan Asia, serta melelehnya ratusan miliar ton es di Greenland dan Antartika hanyalah beberapa di antaranya. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi peningkatan bencana ekologis di luar kelaziman dalam 10 tahun terakhir. Bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan, diperkirakan telah terjadi di 90 persen wilayah Indonesia. Selain berdampak pada terjadinya cuaca ekstrem, pemanasan global juga memberi dampak kepada lingkungan, pertanian, dan kesehatan. Contohnya nyata, mulai dari kualitas air dan produktivitas pertanian menurun, kepunahan ragam spesies yang mengancam keanekaragaman hayati, serta munculnya berbagai wabah penyakit merupakan dampak lebih lanjut dari perubahan iklim. Upaya IndonesiaIndonesia menargetkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030 dengan business as usual atau mencapai 41 persen jika mendapat dukungan internasional. Mengutip Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), secara nasional, target penurunan emisi pada 2030 berdasarkan Nationally Determined Contribution (NDC) adalah sebesar 834 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada target unconditional dan sebesar 1.081 juta ton CO2e pada target conditional. Komitmen pemerintah Indonesia dalam menekan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim diwujudkan melalui berbagai strategi inovatif. Salah satunya dengan mengembangkan Solusi Iklim Alami atau Natural Climate Solutions (NCS). Berdasarkan publikasi di pnas.org, penelitian ilmiah Bronson Griscom dan kawan-kawan pada 2017 bertajuk “Nature Climate Solution” menyimpulkan bahwa Solusi Iklim Alami merupakan strategi yang inovatif dan efektif secara biaya. Solusi Iklim Alami merupakan serangkaian upaya mitigasi berbasis sumber daya alam yang mencakup perlindungan hutan dan lahan basah, perbaikan pengelolaan hutan, serta restorasi ekosistem hutan, gambut, dan mangrove. Solusi tersebut memiliki potensi untuk memberikan kontribusi hingga 90 persen dari target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia jika diimplementasikan secara optimal. Dengan potensi setinggi itu, Indonesia pun optimistis dapat mencapai target penurunan emisi nasional pada 2030. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) telah melakukan riset menggunakan pendekatan Solusi Iklim Alami. Tujuannya, untuk menghitung potensi maksimum penurunan emisi dan analisis biaya dari delapan strategi solusi iklim alami yang dipilih. Riset tersebut dilakukan dengan menggunakan baseline data tingkat nasional atau provinsi selama sepuluh tahun terakhir dan data faktor emisi yang dibangun dari hasil meta-analisis berdasarkan kumpulan studi terkait di Indonesia. Dari data-data tersebut, potensi penyerapan atau pelepasan karbon dari masing-masing ekosistem dan strategi dapat diperkirakan. Untuk diketahui, pendekatan Solusi Iklim Alami di Indonesia mencakup delapan strategi, yaitu pencegahan konversi hutan, reforestasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari, pencegahan dekomposisi gambut dan hilangnya vegetasi akibat perubahan hutan gambut, pembasahan kembali lahan gambut yang terdegradasi, pencegahan kebakaran gambut, pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, dan restorasi ekosistem mangrove. Berdasarkan perhitungan, potensi penurunan emisi di Indonesia dari NCS adalah sebesar 1,47 gigaton CO2e per tahun. Rinciannya, potensi dari ekosistem mangrove berkontribusi sebesar 3 persen, sektor kehutanan 30 persen, dan gambut 67 persen. Dalam penghitungan emisi, dua parameter penting tercakup di dalamnya, yaitu data aktivitas atau potensi luas arealnya dan faktor emisi atau flux. “Dua parameter ini yang menentukan seberapa besar serapan karbon jika program restorasi atau rewetting dilakukan atau berapa emisi yang dirilis ke atmosfer ketika suatu areal hutan mengalami perubahan tutupan lahan atau terjadinya kebakaran,” ujar Forest Carbon and Climate Specialist Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Nisa Novita saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/4/2021). Gambut sebagai salah satu prioritas IndonesiaIndonesia sendiri memiliki lahan gambut seluas 15 juta hektare. Dengan lahan seluas itu, simpanan karbon lahan gambut Indonesia setara dengan 84 persen karbon gambut di seluruh Asia Tenggara. Kendati demikian, tingginya tingkat konversi lahan gambut mengubah potensi gambut sebagai penyerap karbon menjadi pelebas karbon. Lahan gambut di Indonesia kerap digunakan untuk berbagai kegiatan perkebunan dan hutan tanaman industri, seperti sawit, akasia, atau karet. Saat hendak dialih fungsi, lahan gambut perlu dikeringkan. Hal ini menimbulkan bahaya. Sebab, lahan gambut yang dikeringkan akan membuatnya mudah terbakar dan melepaskan karbon secara terus-menerus sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Dalam berbagai kasus, nyatanya manusia justru mengubah gambut yang berfungsi sebagai penyerap karbon menjadi pelepas karbon. Berdasarkan perhitungan NCS, restorasi dan pencegahan dampak gambut berpotensi mengurangi emisi hingga 1.000 megaton CO2e per tahun. “Kami melihat lahan gambut berpotensi paling besar dalam penurunan emisi dibandingkan ekosistem lain. Maka dari itu, kami menelaah lebih lanjut dan melihat ada empat strategi mitigasi iklim di lahan gambut,” ujar Nisa. Dijelaskan oleh Nisa, empat langkah mitigasi tersebut mencakup pencegahan hilangnya vegetasi karena deforestasi hutan, pencegahan emisi dari kebakaran gambut, pencegahan dekomposisi gambut, dan rewetting atau pembahasan kembali gambut yang terdegradasi. Program restorasi ini biasanya juga diikuti dengan penanaman kembali pohon-pohon endemik gambut atau tanaman yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. “Kami menghitung berapa potensi emisi yang terjadi pada dekomposisi gambut jika terjadi gangguan, baik itu deforestasi, degradasi, kebakaran, dan juga jika dilakukan perbaikan pengaturan hidrologi gambut melalui rewetting,” kata Nisa. Dari hasil kajian YKAN, tambah Nisa, pencegahan kerusakan lahan gambut dari alih fungsi hutan, dekomposisi, dan kebakaran memiliki potensi penurunan emisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan penurunan emisi dari rewetting. Dengan kata lain, restorasi gambut memang merupakan langkah penting sebagai upaya perbaikan gambut yang sudah terdegradasi. Meski demikian, jangan lupa perlindungan ekosistem gambut jauh lebih penting dari segi potensi penurunan emisi. Pasalnya, sekali gambut dirusak atau dikeringkan, emisi akan terus dihasilkan kecuali ekosistem ini direstorasi menjadi kondisi yang mendekati ekosistem gambut alami. “Meski hanya mencakup 3 persen dari wilayah daratan bumi, lahan gambut tropis menyimpan sepertiga total karbon dunia. Melestarikan dan melindungi gambut dapat menjadi langkah efektif untuk mitigasi perubahan iklim dan menyelamatkan keberlangsungan peradaban manusia di masa depan,” jelas Nisa. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate) merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Perpres No.109/2020. Meskipun program ini ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sejumlah kajian menilai pendekatan food estate tidak efektif dan belum menyentuh akar permasalahan. Program food estate di Kalimantan Tengah menjadi sorotan karena dikembangkan di lahan eks-pengembangan lahan gambut (PLG) yang gagal di era Presiden Soeharto. Lahan gambut berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ekosistem ini dapat menyimpan karbon 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan hujan tropis atau tanah mineral. Lahan gambut juga menyimpan sekitar 10% cadangan air tawar dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di sisi lain, gambut sangat rentan terhadap gangguan. Lahan gambut dikategorikan sebagai lahan marjinal karena dalam kondisi alaminya, gambut memiliki kesuburan yang rendah, pH yang sangat masam, dan selalu tergenang. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan lahan ini akan digunakan untuk pengembangan food estate. Hingga tulisan ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan lokasi detail mengenai kawasan eks-PLG yang akan digunakan untuk program ini. Informasi yang beredar hanya sekadar lokasi umum. Tetapi belum ada informasi detail sehingga menyulitkan masyarakat sipil dan akademisi dalam melakukan analisis risiko terjadinya alih fungsi lahan gambut dan hutan. Kurangnya informasi ini dapat menghambat pemantauan pengembangan lahan di atas gambut serta dapat memicu adanya konflik antara masyarakat dengan pihak yang terlibat dalam program tersebut. Berikut adalah hasil analisis kami mengenai tiga jenis kawasan gambut yang perlu dihindari dalam pengembangan food estate: 1. Lahan gambut dengan kedalaman > 1 meterLahan gambut berkategori kedalaman sedang sampai sangat dalam (> 1 meter) memiliki daya menahan beban yang rendah, sehingga tidak dianjurkan sebagai lahan pertanian. Karena memiliki tingkat kesuburan yang rendah, lahan ini juga sangat bergantung pada lapisan mineral di bawahnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Di sisi lain, semakin dalam gambut, semakin banyak pula cadangan karbonnya. Gambut berkedalaman 12 meter dapat menyimpan cadangan karbon hampir 22.3 Gt, sehingga potensi kehilangan karbon semakin besar apabila diubah menjadi lahan pertanian. Singkatnya, semakin dalam gambut, semakin rendah potensinya untuk budidaya tanaman pangan.  Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP, 2019) 2. Lahan gambut bervegetasi hutan (primer dan sekunder)Vegetasi hutan rawa gambut memiliki peranan penting dalam menjaga agar ekosistem ini tetap utuh dan menjadi salah satu dari tiga komponen kunci, selain tanah gambut dan air. Dengan utuhnya vegetasi hutan rawa gambut, keseimbangan hidrologis dan keutuhan tanah gambut akan terjaga.  Sumber: Wetlands International (2018) Penggunaan lahan gambut untuk aktivitas pertanian biasanya diawali dengan penyiapan lahan, yang biasanya dilakukan dengan penebangan vegetasi alami hutan rawa gambut sekaligus pembuatan kanal-kanal drainase. Ini adalah awal dari degradasi lahan gambut berupa penurunan muka air tanah, dekomposisi tanah gambut, emisi gas rumah kaca, hingga penurunan permukaan tanah gambut. Emisi karbon yang terukur pada lahan gambut terbuka tanpa vegetasi sebesar 62,25 ton CO2/ha/tahun, setara dengan membakar lebih dari 26.000 liter bensin. Vegetasi rawa gambut asli memiliki kerapatan biomassa yang tinggi, berkisar antara 56 sampai 200 ton karbon/hektar, hampir sama dengan hutan primer di lahan mineral dan 40 kali lebih besar dari cadangan karbon lahan padi. Hilangnya vegetasi alami hutan rawa gambut yang disertai dengan kegiatan drainase menyebabkan gambut kehilangan kemampuan alaminya untuk menyimpan karbon dan menyerap air. Dalam kondisi ini, gambut akan menjadi kering dan sangat mudah terbakar jika terkena percikan api, sehingga tidak hanya menghasilkan karbon, tetapi juga gas-gas rumah kaca lainnya, seperti metana, yang 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida.  Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2019) 3. Lahan gambut dengan fungsi lindungPP No.71/2014 jo. PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut membedakan dua fungsi ekosistem gambut, yaitu fungsi lindung dan fungsi budi daya. Fungsi lindung terkait dengan perlindungan dan penyeimbangan tata air serta penyimpan karbon di suatu kawasan gambut. Ketika fungsi ini mengalami kerusakan, ekosistem menjadi rentan terdegradasi sehingga bencana kebakaran lebih mudah terjadi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang kriteria dalam mengubah fungsi lindung gambut menjadi fungsi budi daya. Namun, pemerintah wajib menetapkan kawasan ekosistem gambut dengan fungsi lindung paling sedikit seluas 30% dari seluruh kesatuan hidrologis gambut (KHG)1. Jadi, lahan gambut di dalam dan luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung tetap harus dilindungi. Kebijakan food estate yang mengubah kawasan hutan tanpa memerhatikan fungsi lindungnya bertentangan dengan peraturan tersebut. Menurut Permen LHK No. 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui perubahan peruntukan kawasan hutan atau melalui penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP). Namun, kriteria dalam kedua cara tersebut tidak mengecualikan kawasan hutan yang merupakan lahan gambut dengan fungsi lindung. Dengan demikian, ada potensi dibukanya lahan gambut dengan fungsi lindung untuk kegiatan food estate. Kebijakan ini juga dapat mengakibatkan alih fungsi ekosistem gambut lindung di luar kawasan hutan lindung, termasuk kawasan hutan produksi (KHP) dan areal penggunaan lain (APL). Menurut analisis WRI, terdapat sekitar 883.475 ha lahan gambut dengan fungsi lindung yang berada dalam kawasan eks-PLG, dimana 92% berada di hutan konservasi dan lindung, 4% berada di hutan produksi, dan 4% berada di APL.  Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2019) Peta No-Go Zone Kawasan Eks-PLG Peta “no-go zone” adalah peta indikatif kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang perlu dilindungi dan dihindari dalam pengembangan program food estate dengan menganalisa tiga kriteria kawasan di atas. Dari hasil peta no-go zone tersebut terindikasi bahwa luas wilayah yang sebaiknya dihindari untuk dijadikan lahan pertanian adalah 1.091.973,67 hektar (74%) dari seluruh total kawasan eks-PLG (1.473.180,4 hektar).  Sumber: Analisis Tim WRI Indonesia Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut sebaiknya dilakukan dengan pendekatan berbasis KHG, karena ekosistem ini merupakan tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. Hal ini penting dilakukan untuk melestarikan dan mencegah terjadinya kerusakan fungsi ekosistem gambut. Belajar dari kegagalan proyek PLG serta dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan percepatan degradasi gambut, sudah selayaknya pemerintah lebih berhati-hati dalam penggunaan lahan gambut untuk food estate. Pembukaan gambut sebagai lahan pertanian tanpa perlakuan khusus akan membuat kondisi ekosistem alami gambut yang basah menjadi kering sehingga meningkatkan potensi kebakaran dan degradasi lahan. Melakukan aktivitas pertanian di lahan gambut sepatutnya memperhatikan hal-hal berikut: a. Manfaatkan lahan budi daya dan lahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya, serta tidak mengonversi gambut menjadi lahan pertanian berdasarkan ketiga jenis kriteria di atas; b. Penuhi kaidah ramah gambut dalam praktik budi daya tanaman, yakni dengan tidak mengeringkan atau membakar gambut serta tidak mencemari lingkungan; c.Lakukan kajian dan analisis dampak lingkungan yang lebih komprehensif terkait kondisi lahan gambut dan kawasan di sekitarnya dengan secara spesifik memperhatikan satu kesatuan lanskap hidrologis gambut; serta d.Amandemen Permen LHK No. 24/2020 dengan penambahan larangan yang jelas pada pembukaan kawasan hutan yang mempunyai lahan gambut dengan fungsi lindung dan mempertimbangkan kriteria biofisik. |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#4
#5
#6
#7
Top 8 apa itu benedict dan biuret? 2022
1 years ago#8
#9
#10
Top 6 apa itu self pick up grabfood? 2022
1 years agoPeriklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 toptenid.com Inc.