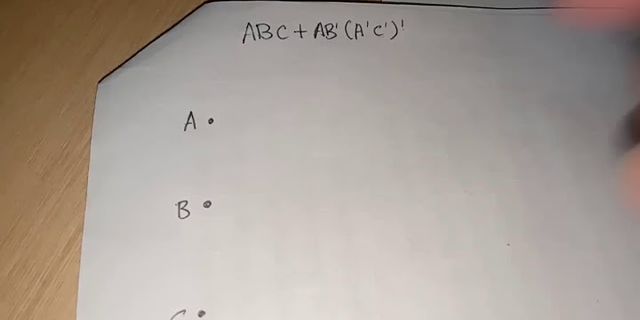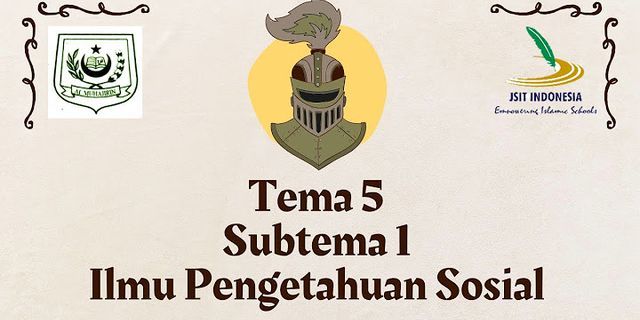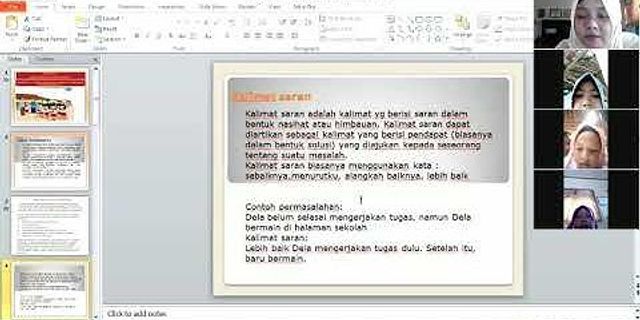UNAIR NEWS – Laut Cina Selatan (LCS) merupakan wilayah strategis, bila ada konflik dari negara yang bersengketa tentu dampaknya akan merugikan negara-negara ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Makarim Wibisono dalam diskusi reboan yang bertajuk “Posisi Indonesia dan Peran ASEAN dalam Konflik Laut Cina Selatan” di Aula Adi Sukadana FISIP UNAIR, Rabu (1/6). Show “Wilayah konflik bisa dimanfaatkan kekayaan lautnya, berupa perikanan maupun kandungan tambangnya oleh pihak-pihak yang mengklaim. Negara Asia Tenggara umumnya menginginkan LCS tetap menjadi wilayah perdamaian,” ujar Guru Besar Hubungan Internasional (HI) UNAIR tersebut. Prof Makarim juga menyayangkan ketiadaannya kejelasan mengenai koordinat lokasi yang akurat dari nine dash line (Sembilan titik lokasi yang menunjukkan klaim China atas wilayah Laut Cina Selatan). Padahal, menurut hukum internasional setiap klaim atas suatu wilayah harus ada kejelasan lokasinya. “Tidak ada kepastian berapa lintang utaranya, berapa bujur timurnya,”serunya. Dalam diskusi tersebut, orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tersebut mengingatkan konsekuensi konflik LCS bagi ASEAN. Selain menurunkan minat FDI (Foreign Direct Invesment) untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN, konflik LCS juga berkonsekuensi menimbulkan persaingan kekuatan militer, sehingga mengalihkan daya ekonomi serta mengundang masuknya negara besar untuk saling mencari pengaruh. “Hal ini akan menjadikan negara-negara yang kurang daya dalam militer untuk melakukan aliansi dengan negara-negara kuat,” ujar Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007 tersebut. Dalam sengketa LCS, Prof. Makarim mengungkapkan bahwa masing-masing pihak bersengketa menginginkan agar negara-negara ASEAN berada dipihak negara bersengketa. Prof Makarim mencontohkan dalam KTT ASEAN, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi, bertemu dengan Menlu Laos, Kamboja, dan Myanmar untuk membicarakan sengketa tersebut, sedangkan Amerika Serikat melobi ke negara Filipina. Dampak Konflik dan Peran Indonesia Prof Makarim menjelaskan, walaupun konflik tersebut masih dikategorikan sebagai konflik Ide, Indonesia diharapkan tetap mengusahakan agar konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh pihak terkait. Hal tersebut untuk menciptakan iklim kondusif dalam mencapai kesepakatan. Jika hal tersebut gagal, maka akan berakibat fatal. Pertama akan berdampak pada lalu lintas perdagangan dan ekonomi Indonesia dengan negara partner, seperti tujuan ekspor maupun negara asal dari penanaman modal. Kedua, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan menjadi wilayah yang tidak stabil. Ketiga, Jika LCS sudah berkembang menjadi konflik secara fisik, maka akan ada campur tangan dari negara-negara besar. “Karena diwilayah konflik, negara besar itu ingin memiliki jaminan untuk bebas melewati LCS. Misalnya saja kapal tangker atau kapal ekspor dari AS gak boleh lewat situ kan berarti dia harus lewat Afrika, secara ongkos memang lebih mahal, itu akan membuat mereka untuk mengusahakan agar jangan sampai terjadi situasi yang menghalangi lalulintas mereka,”tandasnya. Menurut Prof. Makarim, Indonesia bisa menjadi pemimpin Ideal bagi ASEAN yang masih berpotensi untuk mendorong terjadinya penyelesaian sengketa secara damai. Ada tiga alasan yang mendasarinya, pertama, Indonesia yang masih memiliki posisi kondisif bukan merupakan negara Claimant State layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Kedua, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. “Indonesia itu terbesar di ASEAN, baik penduduknya, wilayahnya bahkan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia saja terbesar di ASEAN,” ujar Profesor kelahiran 8 Mei 1947 tersebut. Sedangkan Alasan yang ketiga, dalam sejarah di masa lampau, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Menurut Prof. Makarim, Negara Indonesia hendaknya menghimbau kepada negara yang ikut mengklaim supaya ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct. “Kalau sudah ada Code of Conduct, maka sudah ada rujukan untuk mendamaikan, karena code of conduct itu berisi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kita ada pegangan secara hukum untuk menciptakan perdamaian di wilayah laut cina selatan,”serunya. (*) Penulis : Dilan Salsabila Save the publication to a stack Like to get better recommendations The publisher does not have the license to enable download RUANGNEGERI.com – Pandemi Covid-19 sepertinya tidak serta-merta menghentikan dinamika sengketa Laut China Selatan. Dalam kurun enam bulan terakhir, setidaknya tercatat telah terjadi empat insiden penting di wilayah sengketa. Mengutip Reuters (04/04/2020), rentetan peristiwa dimulai April dengan insiden penenggelaman kapal nelayan Vietnam oleh China di dekat kepulauan Hoang Sa. Pada waktu itu, kapal penelitian negeri Tirai Bambu tersebut sengaja menabrak kapal nelayan Vietnam ketika tertangkap melewati batas wilayah. Insiden berlanjut ketika China mengoperasikan kapal Aircraft Carrier Liaoning di sekitar wilayah sengketa tersebut. Puncaknya adalah dengan sikap Beijing dalam membentuk wilayah administrasi baru dengan memasukkan wilayah yang disengketakan. Kejadian ini mengundang keprihatinan dari beberapa pihak, lantaran terjadi di tengah masa pandemi virus. Tidak hanya prihatin, berbagai pihak juga meningkatkan kewaspadaan mereka untuk mengantisipasi konfrontasi lanjutan. Melansir Foreign Policy (14/02/2020), Filipina telah memutuskan untuk menunda penghapusan Visiting Force Agreement dengan AS. Meski tidak mengakui adanya hubungan langsung, diduga kuat penundaan ini berhubungan dengan manuver China. Vietnam juga mengeluarkan langkah keras. Kementerian Agrikultur Vietnam menyatakan akan menabrak larangan Pemerintah China untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Laut China Selatan. Sebelum peristiwa penabrakan kapal, Vietnam bahkan sudah menyatakan keinginannya memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS. Hal ini termuat dalam Buku Putih Pertahanan Vietnam yang dipublikasikan tahun 2019. Peristiwa ini menjadi bagian panjang dari sengketa Laut China Selatan yang berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Sengketa yang berlangsung sejak 1974 ini melibatkan China, Vietnam. Filipina serta Malaysia dan Brunei. Baca juga: George Floyd, Black Lives Matter dan Ancaman Rasisme Akar dari sengketa ini adalah klaim historis atas sembilan garis putus yang dinyatakan oleh China. Sembilan garis putus (Nine-dash line) ini meliputi wilayah kepulauan Spratly dan Paracel hingga kepulauan Pratas serta karang Macclesfield. Klaim sembilan garis putus China pertama kali dipublikasikan pada tahun 1947 dalam wujud peta resmi wilayah administrasi China. Status sembilan garis putus ini kemudian diperkuat dengan deklarasi laut teritorial pada 1958. Tidak terbatas pada sengketa wilayah, kepentingan ekonomi diduga turut terlibat di dalamnya. UNCTAD (Badan PBB terkait Perdagangan), bahwa 80 persen volume perdagangan dunia melewati Laut China Selatan setiap tahunnya. Jumlah pelayaran tersebut ditaksir mencapai angka perdagangan hingga US$3,37 triliun. Potensi sumber daya alamnya juga tidak kalah menggiurkan. Pada 2016 lalu, United Nations Geological Survey memperkirakan adanya keberadaan 22 miliar barel cadangan minyak, dan 10 triliun kubik gas alam mengendap di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, China telah membangun sedikitnya tujuh pulau buatan di berbagai wilayah kepulauan Spratly. Ketujuh pulau tersebut diyakini diperlengkapi dengan fasilitas militer seperti misil anti kapal dan misil anti pesawat. Pembangunan pulau buatan ini lantas mendapat kecaman dari pihak penyengketa hingga AS. Melansir Straits Times (14/11/2017), Perdana Menteri China, Li Keqiang, bersikukuh bahwa pembangunan fasilitas militer ditujukan untuk “menjaga kebebasan berlayar”. Baca juga: Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods Orang nomor dua di Partai Komunis China tersebut juga menyatakan jika AS sama sekali tidak mempunyai hak mencampuri urusan domestik China. Terkait betapa pentingnya kawasan yang kini menjadi sengketa, pulau-pulau tersebut memegang peranan vital bagi kemampuan militer China di kawasan untuk menghalau kekuatan Amerika Serikat dari wilayah tersebut. Kehadiran AS menjadi keniscayaan sejak Obama mengeluarkan kebijakan “Pivot To Asia” pada 2012 silam. Obama kemudian mengeluarkan kebijakan FONOP (Freedom of Navigation Operation) pada 2015 sebagai tindak lanjut patron politik luar negerinya. FONOP (Freedom of Navigation Operations) memberi wewenang kepada armada laut AS untuk berpatroli di wilayah perairan internasional. Kebijakan tersebut diklaim sebagai upaya untuk menjaga kebebasan berlayar internasional. Pihak militer China sendiri justru memandang FONOP dengan penuh kecurigaan. Menurut mereka, FONOP adalah upaya untuk mengancam kedaulatan negara. Kedatangan armada laut AS, USS Montgomery dalam misi FONOP sempat disambut dengan dua pesawat bomber milik China. Hal ini berbarengan dengan keputusan Presiden Donald Trump yang terus berupaya untuk meningkatkan jumlah misinya. Swee Lean Collin Koh (2019), peneliti pada Institute of Defence and Strategic Studies, Universitas Teknologi Nanyang Singapura, mengatakan bahwa peningkatan aktivitas militer dapat meningkatkan kemungkinan kalkulasi. Risikonya, konflik militer berpotensi terjadi. Tak pelak, hal itu tentulah menjadi kekhawatiran bagi berbagai pihak di kawasan, tak terkecuali bagi Indonesia. Sebagai jalur perdagangan internasional, situasi kondusif Laut China Selatan sangat penting bagi perekonomian negara-negara di sekitarnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia lebih mengambil peran strategis dalam menengahi konflik. Hal ini sangat berpeluang besar. Sebab, dengan fondasi politik bebas aktif yang dimilikinya, Indonesia bisa relatif ‘lebih netral’ dalam menyelesaikan sengketa. Pembukaan UUD 1945 juga menjadi dasar kuat bagi Indonesia, yakni ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan Identitas Politik Bebas Aktif dalam Sengketa Laut China SelatanIndonesia berada dalam posisi ‘unik’ dalam menyikapi sengketa. Indonesia memiliki sejarah panjang tidak pernah memihak dalam berbagai kesempatan, walaupun statusnya sebagai pemimpin (hegemon) alami di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menurutnya tercermin dari belum masuknya penguatan alutsista sebagai prioritas untuk mencapai political bargain di masa lampau. Keputusan untuk tidak memihak memang merupakan inti penting dari konsepsi politik bebas aktif yang dianut selama ini. Politik bebas aktif pada hakikatnya sengaja didesain sebagai pedoman bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip politik ini lahir dari gagasan Bung Hatta yang menginginkan Indonesia “merdeka” sepenuhnya, termasuk dalam urusan politik luar negeri. Hanya saja, tidak mudah menerjemahkan “kemerdekaan” politik luar negeri dalam konteks hari ini. Situasi geopolitik yang kompleks membuat pilihan untuk memihak (alignment) menjadi amat rasional. Kabar baiknya, Indonesia masih sangat mungkin mengaplikasikan politik bebas aktif dalam persoalan ini. Asnani Usman & Rizal Sukma (1997) dalam buku berjudul Konflik Laut China Selatan: Tantangan bagi ASEAN, menyebutkan bahwa Indonesia tergolong sebagai Primus Inter Pares, yakni yang paling utama dalam kawanannya di ASEAN. Indonesia sendiri telah berupaya menjembatani sengketa Laut China Selatan secara aktif sejak 1990. Hal ini dilakukan baik dengan jalur bilateral maupun jalur multilateral. Secara bilateral misalnya, Indonesia secara khusus pernah membicarakan masalah sengketa dengan China melalui perjanjian perluasan kerja sama tahun 2005. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, momentum itu digunakan oleh Indonesia untuk secara resmi meminta China menjalankan Declaration of Conduct of Parties, termasuk menaati perjanjian UNCLOS 1982. Baca juga: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran Di jalur multilateral, Indonesia di bawah payung ASEAN secara aktif melakukan persuasi. Sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia telah aktif mengangkat isu Laut China Selatan baik melalui workshop hingga pembentukan ASEAN Regional Forum. Sementara di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, Indonesia berhasil mengajak China dan sembilan negara ASEAN lainnya menandatangani Declaration of Conduct Parties on South China Sea (DCP) pada tahun 2002. Melalui deklarasi ini, Indonesia berhasil meminta China secara langsung terlibat dalam mitigasi konflik berbasis Confidence Building Measure (CBM). Indonesia terus memelihara manuver diplomasinya melalui ASEAN di era SBY, yakni melalui inisiatif South China Sea Informal Meetings. Langkah-langkah di atas merupakan bagian penting dari pengejawantahan politik bebas aktif. Sayangnya, inisiatif Indonesia belum dapat membuahkan hasil secara nyata. Beijing terlihat masih memilih mengembangkan sikap acuh terhadap komitmen menjaga perdamaian tersebut. Sementara, peran Indonesia sebagai juru damai (honest broker) justru terlihat mendapatkan tantangan dari China sendiri. Salah satunya adalah insiden klaim atas wilayah ZEE Natuna. Pada 2016 saja, tercatat sudah tiga kali insiden antara pihak keamanan Indonesia dengan kapal penjaga pantai Tiongkok. Tantangan atas inisiatif Indonesia juga muncul di internal ASEAN. Dalam beberapa kesempatan, negara anggota ASEAN terbelah terkait persoalan dengan China. Seperti dalam pertemuan di 2016, Kamboja secara terang-terangan menolak komunike bersama yang meminta China tunduk kepada hasil arbitrase. Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda menyatakan bahwa klaim China tidak berbasis hukum. Kamboja memang merupakan salah satu sekutu di Asia Tenggara. Tiongkok diketahui menyumbang sekitar 70 persen dari total investasi luar negeri di Kamboja. Baca juga: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19 Alternatif Penyelesaian SengketaMeski sering menemui jalan buntu, kaidah politik bebas aktif tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan oleh Indonesia. Apalagi politik bebas aktif kita mendapat momentum baik dari visi poros maritim dunia. Sejak dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, visi tersebut menjadi kata yang sakral bagi implementasi kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia (Evan A. Laksmana & Iis Gindarsah, 2018). Dari dalam negeri, kebijakan berorientasi maritim muncul dalam bentuk proyek kapal tol laut serta pengembangan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Sementara, kebijakan luar negeri lebih banyak mengembangkan Diplomasi Maritim. Keduanya berpendapat bahwa Indonesia dapat melakukan pendekatan pada empat formula diplomasi. Empat formula diplomasi tersebut terdiri dari penegakan kepercayaan bersama, pencegahan konflik, pencegahan insiden di laut, hingga pengupayaan perundingan dan perjanjian secara terus-menerus. Meski sulit, salah satu opsi implementasi yang dapat dipilih adalah dengan melibatkan AS dalam pembahasan Code of Conduct. Keterlibatan AS tidak dapat dinafikan, meski bukan merupakan pihak penyengketa. Kekuatan legitimasi negeri Paman Sam, khususnya dalam hal “penegak kebebasan bernavigasi” melalui FONOP, dapat menjadi pertimbangan. Indonesia juga dapat terus aktif mengangkat pentingnya prinsip non-konfrontasi. Hal ini bisa dilakukan dalam setiap kesempatan pertemuan formal maupun informal dengan China. Baca juga: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia Pilihan alternatif lain adalah dengan meningkatkan diplomasi pertahanan. Bhubhindar Singh & See Seng Tan (2011) dalam Jurnal From ‘Boots’ to ‘Brogues,’ The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia, menjelaskan bahwa pelaksanaan diplomasi pertahanan operasi, atau peacekeeping hingga disaster relief berpeluang meningkatkan rasa saling percaya. Jalur konfrontasi langsung sama sekali tidak relevan dengan konsep politik bebas aktif yang kita anut. Terutama, apabila dilihat dari perbandingan alutsista dan faktor strategis lainnya. Sementara, diplomasi Indonesia sudah banyak terbukti melahirkan banyak terobosan-terobosan di dunia internasional. Hal ini pula lah yang menjadi bahan pertimbangan dari masuknya Indonesia sebagai dewan keamanan tidak tetap di PBB. Meskipun tantangan menyelesaikan sengketa Laut China Selatan cukup berat, Indonesia haruslah terus memenuhi konstitusi dasarnya. Yakni, untuk senantiasa terlibat aktif dalam penciptaan perdamaian abadi dan ketertiban dunia. |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#4
#5
#6
#7
Top 8 apa itu benedict dan biuret? 2022
1 years ago#8
#9
#10
Top 6 apa itu self pick up grabfood? 2022
2 years agoPeriklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 toptenid.com Inc.